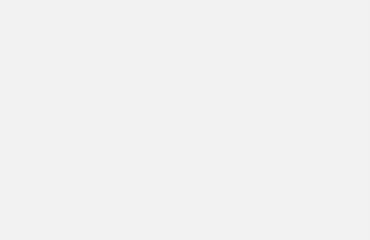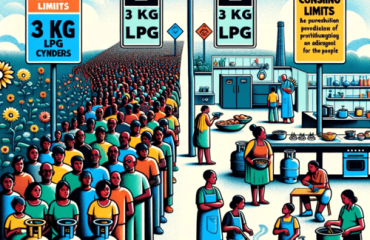Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya lewat DPRD -selanjutnya disebut pilkada tidak langsung- mulanya disuarakan presiden Prabowo Subianto dengan alasan untuk penghematan anggaran negara. Menurut presiden, triliunan rupiah anggaran pilkada dapat dialokasikan untuk pos kebutuhan rakyat lainnya yang dianggap lebih urgen.
Data memang menunjukkan bahwa sejak pelaksanaan pilkada serentak 2017 hingga 2024 lalu, anggarannya mengalami tren kenaikan dengan total keseluruhannya mencapai 80,65 triliun rupiah. Hal ini wajar mengingat wilayah yang masuk pelaksanaan pilkada serentak semakin luas, di mana perhelatan pilkada 2024 diikuti lengkap semua daerah (37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota).
Pilkada serentak 2017 (101 daerah) menelan anggaran 4,2 triliun rupiah, kemudian naik signifikan pada pilkada serentak 2018 (171 daerah) yang menelan anggaran 18,5 triliun rupiah. Biaya yang dikeluarkan kembali naik menjadi 20,4 triliun rupiah pada pilkada serentak 2020 (270 daerah), dan menanjak ke angka 37, 52 triliun untuk pilkada serentak 2024 (545 daerah) yang baru saja berlalu.
Wacana di atas menjadi perdebatan publik setidaknya karena dua hal. Pertama, alasan tersebut mensimplifikasi kompleksitas proses demokrasi, dan cenderung mengesampingkan esensi utama dari pilkada langsung yaitu partisipasi politik warga. Kedua, realitas demokrasi Indonesia yang belum terkonsolidasi paripurna menyebabkan pilihan anggota parlemen tidak serta merta merepresentasikan aspirasi rakyat secara luas.
Melihat efisiensi demokrasi hanya dari segi biaya jelas merupakan pandangan yang sempit. Dalam studi mengenai efisiensi demokrasi (Zimmermann & Just, 2000), misalnya, keberadaan partisipasi politik langsung warga (dalam paper tersebut diambil contoh referendum) justru meningkatkan rasio manfaat kendati menelan biaya ekonomi lebih besar dibandingkan model perwakilan.
Melalui partisipasi langsung, akuntabilitas politik akan meningkat dan mencegah inefisiensi di masa yang akan datang karena kontrol warga terhadap kebijakan lebih besar. Dalam perimbangan cost-benefit, skema pilkada langsung menjadi semacam ‘investasi biaya’ untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kebijakan publik di masa depan. Pada gilirannya, manfaat yang diperoleh menjadi lebih besar meskipun butuh waktu untuk mendapatkan hasilnya.
Selain argumen di atas, salah satu premis yang mendukung skema pilkada tidak langsung memposisikannya pada asumsi demokrasi perwakilan, sehingga dianggap tetap demokratis. Asumsi ‘perwakilan’ menyatakan bahwa warga memberikan ‘mandat’ kepada partai melalui kursi legislatif untuk menjalankan roda kebijakan, termasuk memilih kepala daerahnya. Pernyataan ini patut diuji lebih lanjut, yang kemudian menjadi inti pembahasan dalam utas kebijakan ini.
Jika memang skema pilkada tidak langsung dianggap telah mewakili aspirasi rakyat, idealnya jarak perbedaan terhadap pilihan langsung dari rakyat tidak akan terlalu jauh berbeda. Kenyataan dalam demokrasi Indonesia yang sangat kompleks dan masih tertatih mengkonsolidasikan dirinya, kondisi ideal yang linear seperti itu tidaklah terjadi.
Utas kebijakan ini mencoba untuk melihat secara empiris kesesuaian antara pilihan kepala daerah oleh partai dalam DPRD dengan pilihan langsung dari kotak suara.
Evaluasi reflektif dilakukan terhadap hasil Pilkada 2024 yang perhelatannya baru saja digelar. Pertanyaannya sederhana: berdasarkan hasil Pilkada 2024, bagaimana perbandingan proporsi daerah yang dimenangkan oleh kandidat dengan dukungan (koalisi) partai dari kursi terbanyak dan bukan dari kursi terbanyak di DPRD?